Pernah Ada Larangan Politik Dinasti di Pilkada, tapi Gugur di MK
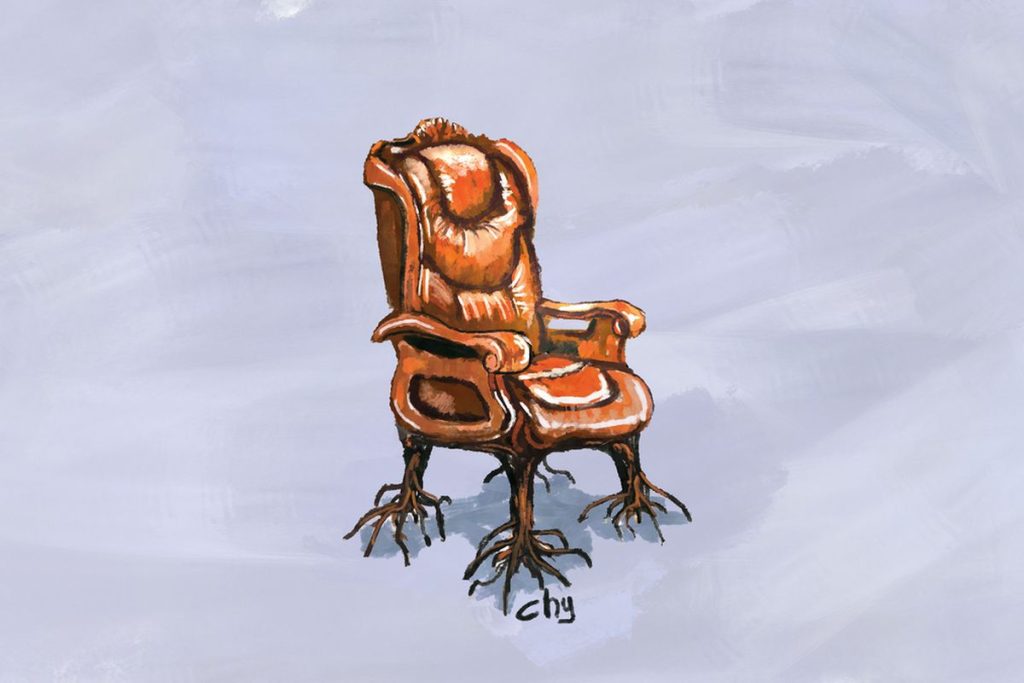
KOMPAS.com - Suami menjabat kepala daerah, istri duduk di bangku parlemen Senayan. Anak menjadi wakil wali kota, ipar memerintah di daerah tetangga. Penguasaan politik di daerah oleh satu garis keturunan atau keluarga tertentu semakin lazim ditemukan di khazanah politik Indonesia. Mirisnya, pemandangan ini bukan hanya terjadi dalam satu atau dua periode kepemimpinan.
Namun, sudah muncul ketika rakyat diberikan kedaulatan untuk memilih pemimpinnya sendiri pasca Orde Baru tumbang pada tahun 1998. Politik dinasti yang begitu kental di beberapa daerah membuat sejumlah pihak cemas dan gerah. Indonesia pernah memiliki aturan untuk melarang merebaknya politik dinasti. Namun, larangan ini tumbang sebelum bisa memberikan jalan bagi rakyat untuk berpolitik dengan lebih sehat.
Awal lahirnya larangan politik dinasti
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) periode 2010–2014, Djohermansyah Djohan, merupakan salah satu tokoh yang menggagas larangan politik dinasti. Prof Djo, panggilan akrabnya, menceritakan bahwa aturan ini berangkat dari kecemasan akan situasi di Indonesia pada tahun 2011. Saat itu, Djo yang masih menjabat sebagai Dirjen Otda Kemendagri mendapatkan paparan data sebaran politik dinasti di Indonesia.
“Ketika pada tahun 2011, kita ingin menyusun UU Pilkada, maka kita menemukan data lapangan, 61 orang kepala daerah dari 524 kepala daerah atau sama dengan 11 persen itu terindikasi menerapkan politik dinasti yang tidak sehat,” kata Djo, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (30/9/2025). Berdasarkan data yang dimilikinya, Djo menemukan banyak daerah yang pemimpinnya berputar di satu keluarga. Misalnya, setelah suami menjabat kepala daerah selama dua periode, istrinya naik untuk mengisi posisi kepala daerah.
Hal ini menjadi bermasalah ketika kepala daerah yang naik tidak memiliki latar belakang pendidikan dan kemampuan yang cukup. Dalam contoh yang disebutkan Djo, istri mantan kepala daerah ini hanya lulusan SLTA dan tidak memiliki pengalaman berorganisasi atau berpolitik. “Suaminya dua periode, kemudian (digantikan), istrinya itu cuma Ketua Tim Penggerak PKK, pendidikannya juga terbatas, cuma SLTA. Nah, banyak kasus itu banyak Ketua PKK jadi wali kota,” imbuh Djo.
Jika bukan sang istri, justru anak kepala daerah yang baru lulus kuliah yang diatur untuk maju pilkada dan menggantikan ayahnya. Anak-anak ‘fresh graduate’ ini kebanyakan tidak memahami birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Akhirnya, ayahnya yang sudah menjabat dua periode ikut campur lagi dan menggerakkan roda kemudi di balik nama anaknya. Djo mengatakan, politik dinasti ini menjadi ladang subur untuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sebab, ketika tidak ada pergantian kekuasaan, pihak-pihak penyokong dan yang dekat dengan pemerintah juga tidak berubah. “Semua pejabat itu yang diangkat bapaknya tetap bertahan, hubungan kontraktor bapaknya tetap bertahan. Jadi, anaknya itu hanya namanya saja sebagai kepala daerah, tapi yang menjalankan pemerintahan tetap bapaknya,” kata Djo. Atas temuan yang ada, Djo dan sejumlah tokoh berusaha untuk menyusun pembatasan politik dinasti saat merancang undang-undang Pilkada.
RUU Pilkada ini melarang anggota keluarga aktif untuk estafet tongkat kepemimpinan. Mereka boleh kembali mencalonkan diri, tetapi perlu ada jeda satu periode setelah kerabatnya aktif di pemerintahan. “Larangan bahwa kalau mau maju pilkada, (kandidat) dari kerabat kepala daerah yang sedang menjabat itu harus dijeda dulu satu periode. Jadi, ketika bapaknya tidak lagi menjadi kepala daerah, boleh silakan maju,” kata Djo.
Ia menegaskan, jika ada kerabat yang maju Pilkada ketika saudaranya masih memerintah, dapat dipastikan akan terjadi keberpihakan. “(Kalau) anaknya maju, bapaknya (yang masih menjabat) kan tolongin anaknya. Mana ada bapak yang enggak nolong anak sama istri di dunia, kecuali hari kiamat,” kata Djo. Larangan ini sempat masuk dalam tatanan hukum Indonesia lewat Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU.
Disebutkan pada Pasal 7 huruf r, calon pemimpin daerah dapat mengikuti suatu pemilihan apabila tidak mempunyai konflik kepentingan dengan petahana. Aturan yang sudah dirancang sejak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat presiden, akhirnya diteken oleh Joko Widodo (Jokowi) di periode pertamanya menduduki kursi RI 1, tepatnya tanggal 18 Maret 2015.
Dibatalkan MK Di hari pengesahannya, pasal ini langsung digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Adnan Purictha Ishan, anak kandung dari Ichsan Yasin Limpo yang saat itu menjabat sebagai Bupati Gowa, Sulawesi Selatan. Ketika mengajukan gugatan ke MK, Adnan tengah menjabat sebagai Anggota DPRD Sulawesi Selatan. Adnan berdalih, Pasal 7 huruf r ini melanggar hak asasi manusia (HAM). Pandangan ini pun diperkuat hakim MK yang mengabulkan permohonan Adnan. Menurut Hakim MK Arief Hidayat, Pasal 7 huruf r bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tak hanya itu, Arief juga menyebutkan, pasal tersebut menimbulkan rumusan norma baru yang tidak dapat digunakan karena tidak memiliki kepastian hukum. “Pasal 7 huruf r soal syarat pencalonan bertentangan dengan Pasal 28 i ayat 2 yang bebas diskriminatif serta bertentangan dengan hak konstitusional dan hak untuk dipilih dalam pemerintahan,” ujar dia, dikutip dari laman resmi MK.
Hakim MK lainnya, Patrialis Akbar, berpendapat, pembatasan terhadap anggota keluarga untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk dipilih atau mencalonkan diri merupakan bentuk nyata untuk membatasi kelompok orang tertentu. MK menyadari, dengan dilegalkannya calon kepala daerah maju dalam Pilkada tanpa adanya larangan memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan petahana, berpotensi melahirkan dinasti politik. Namun, hal ini dinilai tidak dapat digunakan sebagai alasan karena UUD mengatur agar tidak terjadi diskriminasi dan menjadi inkonstitusional bila dipaksakan. Usai dikabulkannya gugatan Adnan, aturan larangan politik dinasti resmi tidak bisa digunakan. Adnan selaku penggugat berhasil memenangkan Pilkada 2016 dan menggantikan ayahnya untuk menjadi Bupati Gowa.
Alasan politik dinasti tumbuh subur
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman mengatakan, politik dinasti marak terjadi karena lahir dari fenomena yang ada. Ia menilai, orang yang mau maju dan eksis di dunia politik di Indonesia perlu dua modal, yaitu modal politik dan modal ekonomi. “Kalau kita bicara dinasti, dia itu punya dua modalitas itu, modalitas politik dan juga modalitas ekonomi,” ujar Armand, saat dihubungi, Selasa (30/9/2025).
Modal politik adalah relasi atau jaringan yang dimiliki seseorang agar bisa mulus masuk ke dunia politik. Sementara, modal ekonomi merujuk pada kemampuan untuk membayar biaya politik. “Yang maju sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah itu adalah kalau dia enggak punya relasi politik, pasti dia juga punya modal ekonomi yang cukup,” kata Armand. Masih maraknya politik dinasti, menurut Armand, akan membatasi akses bagi orang di luar dinasti untuk masuk dan terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Armand mengatakan, politik dinasti itu seperti membangun sebuah tembok dan hanya sebagian kalangan yang bisa masuk ke dalam. “Dinasti politik kan sebetulnya itu dia membangun tembok ya. Membangun tembok terhadap partisipasi non-dinasti terhadap proses perencanaan, proses penganggaran, bahkan dalam proses penyusunan kebijakan di daerah gitu,” ujar dia.
Solusi hadapi dinasti politik
Armand menegaskan, meski secara aturan politik dinasti sudah tidak dilarang, keberadaannya kontraproduktif dengan apa yang hendak dicapai Indonesia. Terutama, dalam upaya penguatan demokrasi lokal dan upaya peningkatan efektivitas serta efisiensi pelayanan publik. Keberadaan politik dinasti juga dinilai dapat menghilangkan fungsi pengawasan atau check and balance antar lembaga. “(Misalnya), salah satu pasangan di (lembaga) eksekutif, pasangannya yang lainnya di DPRD. Itu akan menghambat check and balance di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan itu,” kata dia. Armand menilai, akan lebih efektif untuk meningkatkan literasi politik masyarakat demi meminimalkan dampak politik dinasti.
“Sekarang, dengan diberi peluangnya dinasti itu, sebetulnya yang jadi alat kontrol kita sekarang itu adalah literasi ke publik,” kata Armand. Semakin masyarakat lebih mengenal calon pemimpinnya, peluang untuk memperbaiki kualitas politik juga akan meningkat. Di sisi lain, Armand mendorong adanya reformasi di internal partai politik, yaitu melalui perbaikan sistem kaderisasi. “Bagaimanapun, kalau misalnya sistem kaderisasi atau rekrutmen di politik itu juga berbasis pada kepentingan keluarga tertentu, itu juga kan menyuburkan politik dinasti,” ujar dia.
Armand menegaskan, jika orientasi partai masih sebatas mendorong sanak keluarga atau kerabatnya untuk terpilih, sebatas untuk melanjutkan kekuasaan, politik dinasti tak ayal akan terus ada. Namun, jika yang diprioritaskan adalah kualitas individu, mau berasal dari dinasti atau tidak, semisal ia terpilih, tentu tidak dipersoalkan. “Kemudian, yang ketiga (yang perlu diperbaiki) ya terkait dengan pembiayaan politik,” kata Armand. Ia menilai, salah satu alasan politik dinasti muncul karena mahalnya biaya politik di Indonesia.
Jika politik dinasti ingin dikurangi, biaya politik ini juga harus turun. Mahalanya biaya politik di Indonesia juga menjadi sorotan dari Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati. Neni menilai, tingginya biaya politik membuat aksesibilitas politik menjadi sangat terbatas. “Politik mahal hanya dapat diakses oleh mereka yang sedang berkuasa. Ini sangat bertentangan dengan nilai demokrasi yang sejatinya mendorong aspek inklusivitas,” ujar Neni, saat dihubungi, Selasa (30/9/2025).
Selain memperkuat literasi publik hingga menurunkan biaya politik, Neni berharap aturan untuk membatasi politik dinasti bisa dibahas lagi oleh pemerintah. “Sebetulnya, saya punya harapan besar RUU Partai Politik masuk juga di prolegnas 2026 bersama dengan RUU Pemilu dan Pilkada,” kata dia. Ia menilai, politik dinasti bisa dikurangi jika ada syarat dan ketentuan pencalonan yang diperketat.
Misalnya, seseorang baru bisa maju setelah tiga tahun menjalani kaderisasi dalam sebuah partai politik. Menurut dia, butuh pembekalan yang cukup agar kepala daerah memiliki kapasitas yang baik agar tidak dipertanyakan di muka publik. Lebih lanjut, pembatasan masa jabatan di lembaga legislatif juga perlu diatur. Terlebih, karena jabatan di lembaga eksekutif juga telah dibatasi hanya bisa dua periode. Pembatasan masa jabatan ini dinilai dapat mendorong regenerasi di tubuh partai. Sebab, selama ini, tokoh yang masuk ke DPR atau DPRD bisa menjabat hingga 20-30 tahun. “Selama ini, batasan periodisasi itu tidak ada sehingga partai menjadi institusi bisnis yang menumbuhsuburkan lahirnya politisi, tapi defisit negarawan,” tegas Neni.


